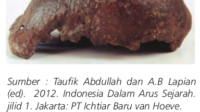Periode pasca-Proklamasi Kemerdekaan Indonesia adalah masa yang penuh gejolak dan perjuangan. Setelah memproklamirkan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 dengan cita-cita luhur negara kesatuan, Indonesia justru harus melalui fase eksperimental yang singkat namun krusial dalam sejarahnya: berbentuk negara federal yang dikenal sebagai Republik Indonesia Serikat (RIS).
Bentuk negara ini hanya berumur jagung, berdiri dari 27 Desember 1949 hingga 17 Agustus 1950, sebelum akhirnya kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pertanyaan mendasar yang sering muncul adalah, mengapa bentuk negara RIS yang federal itu begitu cepat runtuh dan terbukti tidak cocok untuk Indonesia?
Artikel ini akan mengupas secara mendalam faktor-faktor penyebab ketidakcocokan bentuk negara RIS tersebut, menganalisis konteks sejarah, struktur organisasinya, serta sentimen politik dan sosial yang berkembang saat itu. Memahami kegagalan federalisme di Indonesia pada era RIS memberikan pelajaran berharga tentang fondasi kebangsaan dan pentingnya persatuan bagi negara kepulauan ini.
Daftar Isi
Konteks Sejarah Pembentukan RIS: Dari Proklamasi ke Konferensi Meja Bundar
Untuk memahami mengapa bentuk negara RIS tidak cocok, kita harus melihat kembali bagaimana ia terbentuk. RIS bukanlah pilihan sukarela murni dari para pendiri bangsa, melainkan hasil kompromi yang dipaksakan oleh situasi politik dan militer pasca-kemerdekaan.
Cita-cita Awal: Negara Kesatuan
Sejak awal pergerakan nasional hingga proklamasi, para tokoh pendiri bangsa, terlepas dari berbagai perbedaan pandangan, sepakat pada satu hal fundamental: Indonesia harus menjadi satu kesatuan, dari Sabang sampai Merauke. Sumpah Pemuda 1928 adalah manifestasi awal cita-cita ini. Proklamasi 17 Agustus 1945 juga menggarisbawahi lahirnya “Negara Indonesia” yang merdeka dan berdaulat, bukan serikat negara-negara bagian. Undang-Undang Dasar 1945 yang asli pun dirancang untuk sebuah negara kesatuan, di mana kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Semangat persatuan, kesatuan, dan sentralisme yang kuat ini telah tertanam dalam benak sebagian besar rakyat dan elit politik yang berjuang.
Tekanan Eksternal dan Strategi Belanda
Setelah Proklamasi, Belanda tidak serta merta mengakui kemerdekaan Indonesia. Mereka berusaha kembali berkuasa, seringkali melalui cara-cara militer (Agresi Militer I dan II) sambil menjalankan strategi politik “devide et impera” (pecah belah dan kuasai). Salah satu implementasi strategi ini adalah dengan membentuk negara-negara boneka atau daerah otonom di wilayah-wilayah yang berhasil mereka kuasai, di luar wilayah Republik Indonesia yang berpusat di Yogyakarta. Negara-negara seperti Negara Indonesia Timur, Negara Pasundan, Negara Jawa Timur, dan lainnya didirikan dengan dukungan atau inisiasi Belanda. Tujuannya jelas: melemahkan posisi Republik Indonesia dan menciptakan citra bahwa Indonesia tidak homogen dan lebih cocok menjadi negara federal di bawah kendali Belanda.
Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag (Agustus-November 1949) adalah titik kulminasi dari tekanan ini. Dalam KMB, Belanda bersedia mengakui kedaulatan Indonesia, tetapi dengan syarat bahwa bentuk negaranya adalah federal, yaitu RIS, bukan negara kesatuan. Republik Indonesia (yang hanya mencakup sebagian kecil wilayah Jawa dan Sumatera) menjadi salah satu negara bagian dari RIS, bersama dengan 15-16 negara bagian dan kesatuan politik lainnya yang sebagian besar merupakan bentukan Belanda. Terjepit oleh kekuatan militer Belanda dan tekanan internasional untuk mengakhiri konflik, delegasi Indonesia yang dipimpin Mohammad Hatta terpaksa menerima bentuk negara federal ini sebagai syarat untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan penuh. Penerimaan ini adalah langkah taktis, sebuah “jembatan emas” untuk mencapai kemerdekaan de jure, namun mengandung benih-benih ketidakcocokan yang akan segera terlihat.
Struktur dan Karakteristik RIS yang Bermasalah
RIS dibentuk dengan struktur yang kompleks dan mengandung kelemahan fundamental yang membuatnya rentan dan tidak sesuai dengan realitas dan aspirasi Indonesia.
Model Federal yang Dipaksakan
Model federal RIS berbeda dengan federalisme yang tumbuh secara organik dari kebutuhan daerah atau sejarah penyatuan entitas independen (seperti di Amerika Serikat). RIS adalah federasi yang diciptakan dari atas, sebagian besar unit federalnya (negara bagian/daerah otonom) tidak memiliki dasar historis atau kultural yang kuat sebagai entitas politik terpisah, melainkan sengaja dibentuk oleh Belanda. Hal ini menimbulkan kesan kuat bahwa federalisme di Indonesia saat itu adalah warisan kolonial yang dirancang untuk memecah belah persatuan, bukan untuk mengakomodasi keragaman secara sehat. Rakyat dan para pejuang kemerdekaan melihat bentuk federal ini sebagai upaya Belanda untuk tetap mempertahankan pengaruhnya di Indonesia.
Dominasi Elemen Non-Republik Indonesia
Dalam struktur RIS, Republik Indonesia (RI) yang berpusat di Yogyakarta hanyalah salah satu negara bagian, meskipun dianggap yang paling penting secara historis dan politik. Namun, secara jumlah dan potensi fragmentasi, negara-negara bagian bentukan Belanda lebih banyak. Ini menciptakan ketidakseimbangan legitimasi. RI memiliki legitimasi dari perjuangan kemerdekaan dan dukungan rakyat, sementara sebagian besar negara bagian RIS lainnya dipandang sebagai “boneka” Belanda yang tidak memiliki dukungan rakyat yang kuat. Konstitusi RIS (Konstitusi Sementara RIS) memberikan kedudukan yang setara bagi semua negara bagian secara hukum, namun realitas politik menunjukkan ketegangan antara elemen Republik yang pro-NKRI dengan elemen negara bagian yang dicurigai masih pro-Belanda atau anti-Republik.
Pembagian Kekuasaan yang Rancu dan Tidak Merata
Konstitusi RIS menciptakan sistem pemerintahan parlementer dengan lembaga eksekutif (Presiden RIS dan Kabinet RIS) dan legislatif (Senat RIS dan Dewan Perwakilan Rakyat RIS). Namun, pembagian kekuasaan antara pemerintah federal RIS dengan pemerintah negara bagian seringkali tidak jelas dan menimbulkan kerancuan. Ada masalah dalam penentuan kewenangan di berbagai bidang seperti keuangan, pertahanan, dan hubungan luar negeri. Selain itu, struktur parlemen RIS yang terdiri dari Senat (perwakilan negara bagian) dan DPR (perwakilan rakyat) juga mencerminkan kerumitan federasi yang baru lahir ini. Pengambilan keputusan sering terhambat oleh kepentingan negara bagian yang beragam dan seringkali tidak sejalan dengan kepentingan nasional secara keseluruhan, terutama kepentingan unit Republik Indonesia.
Konstitusi RIS dan Kedaulatan yang Terbagi
Konstitusi Sementara RIS (Konstitusi RIS) berlaku sebagai dasar hukum negara federal ini. Meskipun secara formal menyatakan kedaulatan berada di tangan rakyat RIS, kenyataannya kedaulatan ini terasa terbagi-bagi antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian. Lebih jauh lagi, residu pengaruh Belanda masih terasa kuat, terutama melalui masalah hutang yang diwariskan dari KMB dan keberadaan perwakilan tinggi Belanda di Indonesia. Konstitusi RIS ini tidak sejalan dengan jiwa dan semangat UUD 1945 yang menghendaki persatuan dan sentralisasi kekuasaan untuk membangun negara baru yang kuat.
Faktor-faktor Internal dan Eksternal Penyebab Ketidakcocokan RIS
Selain struktur yang bermasalah, beberapa faktor lain, baik dari dalam maupun luar, turut menyebabkan bentuk negara RIS tidak dapat bertahan lama dan tidak cocok dengan konteks Indonesia.
Kurangnya Dukungan Rakyat dan Elit Politik
Faktor paling krusial penyebab ketidakcocokan negara federal RIS adalah minimnya dukungan dari mayoritas rakyat dan sebagian besar elit politik Indonesia. Rakyat melihat bentuk federal ini sebagai kelanjutan upaya penjajah untuk memecah belah bangsa. Gerakan anti-federalis muncul di mana-mana, menuntut pembubaran negara-negara bagian bentukan Belanda dan kembali ke negara kesatuan. Demonstrasi, petisi, dan pernyataan sikap dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari organisasi massa, partai politik, hingga pemerintah daerah (yang masih pro-Republik), secara masif menyuarakan penolakan terhadap federalisme RIS. Para pemimpin Republik, meskipun terpaksa menerima RIS di KMB, secara hati-hati dan strategis terus berupaya untuk kembali ke NKRI. Sosok seperti Mohammad Natsir, misalnya, menjadi motor penggerak mosi integral di parlemen RIS yang menuntut pembubaran negara bagian dan penyatuan kembali ke dalam Republik Indonesia.
Masalah Ekonomi dan Keuangan
RIS mewarisi beban ekonomi yang sangat berat dari hasil KMB, termasuk keharusan membayar hutang-hutang pemerintah kolonial Belanda. Beban finansial ini membatasi ruang gerak pemerintah federal RIS dalam membangun ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Selain itu, pembagian sumber daya dan pendapatan antara pemerintah federal dan negara bagian juga menjadi sumber potensi konflik dan ketidakpuasan, memperparah ketidakstabilan yang ada. Kondisi ekonomi yang sulit di awal kemerdekaan semakin membuat rakyat mempertanyakan efektivitas dan relevansi bentuk negara federal yang rumit ini.
Konflik Internal dan Pemberontakan
Meskipun RIS bertujuan membawa stabilitas melalui pengakuan kedaulatan, bentuk federal yang rapuh justru memicu konflik internal dan pemberontakan di beberapa daerah. Peristiwa seperti pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) di Bandung yang dipimpin Westerling, pemberontakan Andi Azis di Makassar, dan proklamasi Republik Maluku Selatan (RMS) di Ambon adalah contoh konkret dari ketidakstabilan yang muncul di era RIS. Meskipun motif di balik pemberontakan ini kompleks (termasuk isu status tentara KNIL dan loyalitas daerah), keberadaan struktur federal yang lemah dan tidak memiliki legitimasi kuat di mata rakyat memudahkan munculnya disintegrasi dan gerakan separatis. Pemberontakan-pemberontakan ini semakin memperkuat argumen bahwa bentuk negara RIS tidak mampu menjamin stabilitas dan keutuhan wilayah Indonesia.
Semangat Persatuan dan Nasionalisme yang Kuat
Yang paling mendasar, bentuk federal RIS bertentangan dengan semangat persatuan dan nasionalisme yang telah mengakar kuat selama perjuangan kemerdekaan. Cita-cita “satu nusa, satu bangsa, satu bahasa” telah menjadi fondasi identitas kebangsaan Indonesia. Bentuk federal, dengan negara-negara bagian yang terpisah dan seringkali dianggap bentukan asing, dirasakan mengkhianati semangat persatuan ini. Dorongan untuk kembali ke negara kesatuan bukanlah sekadar pilihan struktural, melainkan panggilan jiwa kebangsaan yang kuat, mencerminkan keinginan untuk mewujudkan cita-cita Proklamasi secara utuh.
Peran Tokoh-tokoh Nasional
Para pemimpin dan tokoh nasional memainkan peran sentral dalam menyuarakan dan mengorganisir penolakan terhadap bentuk negara RIS. Melalui jalur politik di parlemen RIS, maupun melalui pengaruh mereka di tengah masyarakat, mereka tanpa lelah memperjuangkan pembubaran negara bagian dan penyatuan ke dalam Republik Indonesia. Mosi Integral Mohammad Natsir pada April 1950 di parlemen RIS, yang mendapat dukungan luas, menjadi momen krusial yang mempercepat proses kembalinya ke NKRI. Ini menunjukkan bahwa elit politik yang memiliki legitimasi perjuangan kemerdekaan secara konsisten menolak federalisme yang dipaksakan ini.
Transisi Menuju Negara Kesatuan: Kembalinya Cita-cita Proklamasi
Melihat gelombang penolakan yang masif dan ketidakstabilan yang melanda, bentuk negara RIS terbukti tidak dapat dipertahankan. Proses kembalinya ke negara kesatuan berlangsung cepat dan relatif mulus, didorong oleh kehendak kuat dari rakyat dan para pemimpin.
Gelombang Penyatuan Negara Bagian
Setelah RIS terbentuk, satu per satu negara bagian (yang sebagian besar tidak memiliki dukungan rakyat) mulai menyatakan keinginan untuk bergabung dengan Republik Indonesia yang berpusat di Yogyakarta. Proses ini seringkali dipicu oleh demonstrasi rakyat dan tekanan politik di wilayah tersebut. Pemerintah RIS yang federal tidak mampu membendung gelombang penyatuan ini karena ketiadaan legitimasi dan kekuatan riil. Dalam beberapa bulan saja, sebagian besar negara bagian RIS telah meleburkan diri ke dalam wilayah Republik Indonesia.
Proklamasi Negara Kesatuan (17 Agustus 1950)
Puncaknya, pada 17 Agustus 1950, bertepatan dengan peringatan lima tahun Proklamasi Kemerdekaan, Indonesia secara resmi kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembubaran RIS dan pembentukan kembali NKRI dilakukan berdasarkan Undang-Undang Federal Nomor 7 Tahun 1950 tentang Perubahan Konstitusi Sementara RIS menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia. Peristiwa ini disambut dengan suka cita oleh seluruh rakyat Indonesia, menandai kembalinya kepada cita-cita awal kemerdekaan dan penolakan tegas terhadap upaya pemecahbelahan bangsa melalui struktur federal yang dipaksakan. Kembalinya ke NKRI memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, menjadi fondasi bagi pembangunan negara di masa mendatang.
Kesimpulan
Analisis mendalam mengenai bentuk negara RIS menunjukkan bahwa struktur federal tersebut memang tidak cocok untuk Indonesia. Kegagalan federalisme di Indonesia pada era RIS disebabkan oleh kombinasi faktor historis, politis, sosial, dan struktural. RIS bukanlah pilihan organik yang tumbuh dari kebutuhan internal Indonesia, melainkan hasil kompromi yang dipaksakan oleh kekuatan eksternal, terutama Belanda, sebagai bagian dari strategi mereka untuk mempertahankan pengaruh. Struktur federal RIS yang artifisial, keberadaan negara-negara bagian bentukan Belanda yang tidak memiliki legitimasi kuat, serta pembagian kekuasaan yang rancu, semuanya berkontribusi pada rapuhnya bangunan negara ini.
Namun, faktor terpenting yang menyebabkan bentuk negara RIS tidak cocok dan akhirnya bubar adalah kuatnya semangat persatuan dan nasionalisme di kalangan rakyat dan elit politik Indonesia. Cita-cita negara kesatuan yang telah ditanamkan jauh sebelum kemerdekaan dan diikrarkan melalui Proklamasi 1945 jauh lebih kuat daripada bentuk federal yang dipaksakan. Kurangnya dukungan rakyat, masalah ekonomi yang berat, dan munculnya konflik internal adalah gejala dari ketidakcocokan fundamental ini.
Pengalaman RIS memberikan pelajaran berharga bahwa persatuan dan kesatuan adalah pondasi utama negara Indonesia. Bentuk negara yang dipilih haruslah sejalan dengan jiwa kebangsaan dan mampu mengakomodasi keragaman tanpa mengorbankan integritas nasional. Kembalinya ke NKRI pada tahun 1950 menegaskan kembali komitmen bangsa Indonesia terhadap negara kesatuan sebagai wadah yang paling sesuai untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan dan membangun masa depan yang satu dan berdaulat. Mempelajari sejarah bentuk negara RIS adalah memahami betapa berharganya persatuan bagi Indonesia dan mengapa segala upaya pemecahbelahan harus dihadapi dengan semangat kebangsaan yang tak tergoyahkan.